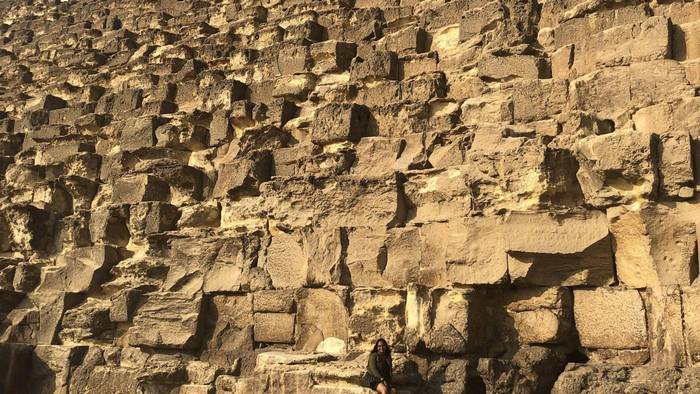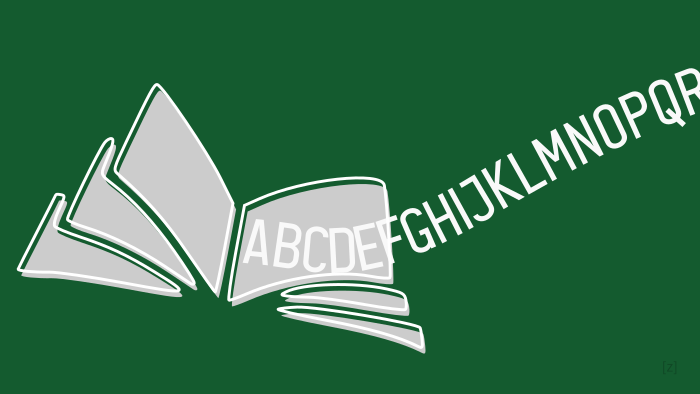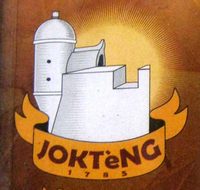\
Aah… Nya’ banjir!
Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk
Ruméh ané kebakaran garé-garé kompor meleduk
Ané jadi gemeteran, wara-wiri keserimpet
Rumah ané kebanjiran gara-gara got mampet“Kompor Mleduk”. Benjamin S., 1970.
Jakarta kelihatannya terancam kebanjiran lagi, meskipun Pak Jokowi sudah blusukan hampir setiap hari. (( Update: paruh terakhir Desember 2012, beberapa jalan dan kampung sudah ‘tergenang’. )) Dua tahun lalu, saya merasakan akibat banjir ((Waktu itu disebut sebagai genangan air. )) di Jakarta itu. Jarak yang biasanya ditempuh selama empat puluh menit, dengan transjakarta plus jalan kaki, molor hingga lima setengah jam!
Jika gubernur sudah memikir yang makro–lingkup provinsi dan koordinasi dengan wilayah lain–kita perlu memikir juga tingkat pribadi. Salah satunya adalah dengan persiapan yang baik jika akan bepergian–dengan angkutan umum–agar tidak sengsara.

Ransel yang dapat dibawa sehari-hari rasanya cukup tepat untuk bersiap-siap menghadapi alam yang tak mau kompromi. Ransel dengan berbagai kantong di luar cukup pas untuk keperluan ini, agar kita tidak perlu membuka kantong utama untuk mencari barang tertentu. ((Hanya, kurang tahu apakah ransel lebih rawan pencopetan? )) Ransel dengan raincover akan lebih menghindarkan isi dari basah dan lebih mengamankan dari tangan jahil.
Artefak isi ransel
Berikut beberapa benda yang dapat menjadi isi ransel ‘siaga hujan’, untuk para commuter penumpang kendaraan umum seperti transjakarta.
- Botol tentu dengan air minum isinya. Meski naik bis di Jakarta dan bukan naik unta di gurun, kita bisa saja dehidrasi. Oleh karena itu, siapkan air minum yang mudah dibawa. Letakkan di kantong samping ransel agar mudah dijangkau. Lalulintas sering macet, apalagi jika hujan dan kemudian banjir. Tidak setiap halte transjakarta terdapat mesin penjual minuman.
- Payung atau jas hujan. Terutama jika kita harus berjalan dari angkutan umum ke kantor atau rumah dan sebaliknya. Tepat kata pepatah: “Sedia payung sebelum hujan.”
- Sandal jepit. Benda ini berguna jika terpaksa harus berjalan di genangan air. Sayang, kan sepatu kita (itu jika kita mengenakan sepatu, lho). Atau sejak awal kita sudah mengenakan sepatu karet, seperti merk yang populer itu. Benda berguna ini kadang dijual di jembatan transjakarta. Tetapi, sebaiknya memang selalu mengenakan sepatu untuk melalui air banjir, sebagaimana anjuran IDI ((http://health.kompas.com/read/2013/01/17/14161695/IDI.Selalu.Gunakan.Sepatu.ke.Lokasi.Banjir))
- Alat komunikasi. Bisa memberitahu keluarga bahwa kita perlu dijemput di suatu tempat atau memberitahu bahwa keadaan kita baik-baik saja, hanya sedang berada dalam kendaraan yang tidak dapat bergerak. Ibu-ibu mungkin harus menidurkan putra-putri mereka yang di rumah dengan menelepon dari bis. Bagus juga jika kita memberitahu kepada khalayak–lewat jejaring sosial–tentang kondisi lalu lintas dan jalan.
- Benda pembunuh waktu. Jika terpaksa menunggu lama, kita dapat memanfaatkan waktu dengan mengerjakan sesuatu yang berharga (membaca buku, membuat rajutan) … atau sekedar menghilangkan kebosanan dengan mendengar lagu dari peranti mp3 ((Tentu headphone atau earphone diperlukan. Mungkin tetangga duduk kita di bis tidak suka lagu kita, atau lagi beda mood … )) atau memutar-mutar kotak rubik yang belum terpecahkan. Lumayan, daripada manyun.
Dua benda terakhir ini dapat diringkas menjadi satu: telepon genggam, benda ajaib di abad ke-21 ini. Entah, saya belum tahu ada ponsel yang dapat menjadi payung atau sandal. ((Jangan keliru dengan tempat air minum berbentuk telepon genggam… hehehe. )) [z]
Ayo-ayo bersihin got Jangan takut badan blépot
Coba elu jangan ribut Jangan padé kalang kabut
- Baca juga: Darurat Banjir
Catatan kaki